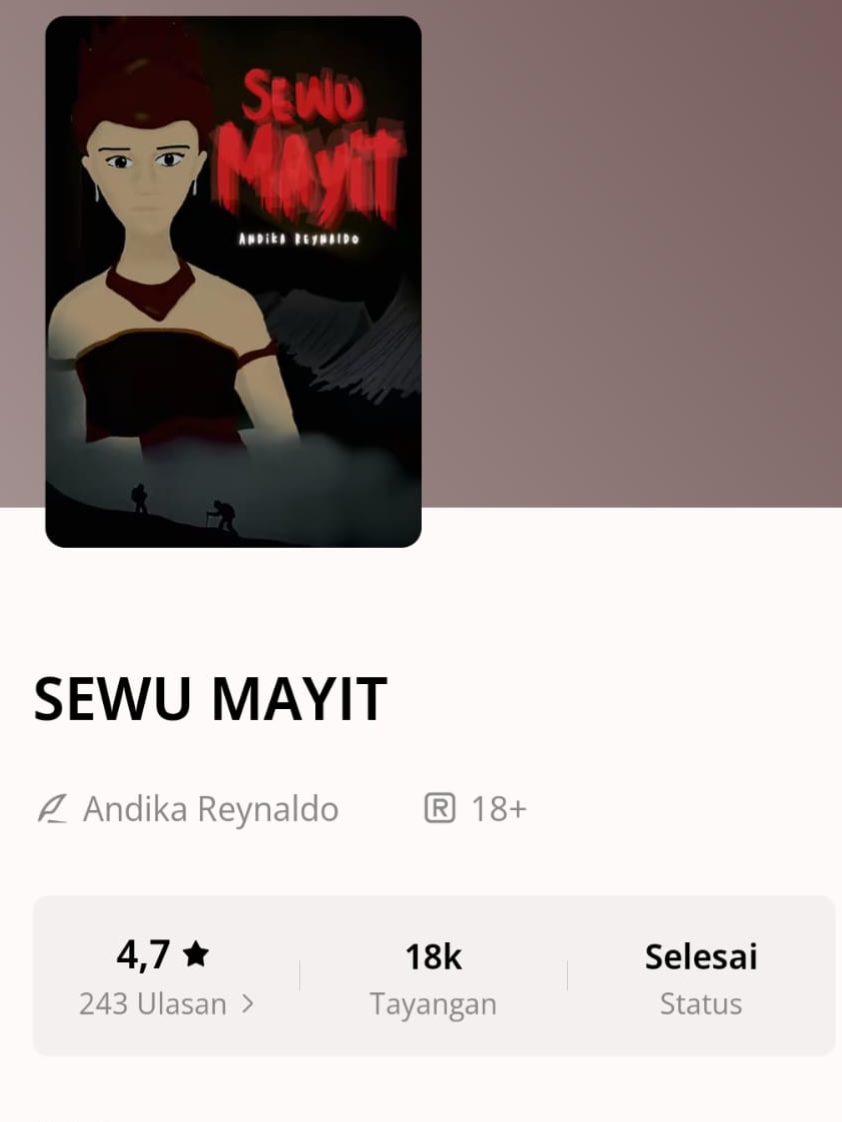Opini, Inspiratifonline.com – Pendakian gunung kerap kita pahami sebagai perjalanan menuju keindahan. Udara pegunungan yang dingin, pepohonan yang menjulang, dan matahari yang perlahan naik sering dianggap sebagai hadiah bagi mereka yang berani lelah. Gunung, dalam banyak cerita, adalah tempat membersihkan diri. Tetapi kisah Sewu Mayit justru mengingatkan bahwa alam tidak selalu hadir untuk ditaklukkan, apalagi diperlakukan sebagai latar swafoto semata.
Empat pendaki muda, dua pemuda dan dua gadis, pada tahun 1985 merasakan keindahan itu sepenuhnya. Tawa, kehangatan makanan di tenda, dan rasa aman yang muncul ketika berada di puncak membuat segalanya terasa baik-baik saja. Namun seperti banyak kisah horor yang berakar pada tradisi, ketenangan sering kali hanya permukaan. Di bawahnya, ada wilayah yang tidak menunggu untuk dijelaskan.
Keputusan mereka untuk turun melalui jalur berbeda menjadi titik balik. Jalur yang jarang dilalui, bahkan dikenal sebagai jalur terlarang. Bukan karena ia berbahaya secara teknis semata, melainkan karena ia menyimpan larangan kultural. Dalam banyak kebudayaan Jawa, larangan bukan sekadar aturan, tetapi penanda batas antara yang boleh dan yang sebaiknya tidak disentuh.
Baca Juga : Horor yang Bertahan Sepuluh Tahun: “Review Tumbal Pitung Dino”
Kabut turun tanpa permisi. Pandangan terputus. Salah satu gadis menghilang. Tidak ada jeritan dramatis, tidak ada tanda heroik. Ia hanya tersesat, lalu semakin jauh dari apa yang ia kenal. Di titik ini, horor tidak bekerja sebagai kejutan, tetapi sebagai pengalaman batin. Ketakutan tumbuh dari kebingungan, dari hilangnya orientasi, dari rasa sendirian di tengah alam yang tak lagi ramah.
Gapura bambu bertuliskan “Sugeng Rawuh” menjadi simbol yang menarik. Selamat datang. Kalimat yang biasanya menandai keramahan, justru menjadi pintu menuju ketidakpastian. Pasar tradisional yang ramai, kue-kue Jawa, transaksi yang terasa normal, semua hadir seperti dunia yang dikenal. Tetapi keakraban itu rapuh. Ia lenyap seketika, meninggalkan sunyi yang dingin dan menyadarkan bahwa tidak semua yang tampak hidup benar-benar berada di dunia kita.
Baca Juga : Horor yang Tumbuh dari Sunyi, “Misteri Desa Mati”
Sewu Mayit tidak sedang bercerita tentang pasar gaib semata. Ia sedang berbicara tentang batas. Tentang ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki hanya dengan keberanian, apalagi dengan rasa penasaran kosong. Pasar yang muncul lalu menghilang adalah metafora tentang wilayah sakral yang tetap berjalan dengan hukumnya sendiri, meski manusia modern merasa cukup dengan logika.
Di sisi lain gunung, kepanikan rombongan pencari menyadarkan satu hal penting. Jalur yang mereka lalui bukan sekadar jalur tersesat, melainkan jalan menuju Pasar Sewu Mayit, tempat yang secara turun-temurun dilarang untuk dimasuki. Di sini, horor mencapai bentuknya yang paling sunyi. Bukan pada penampakan, melainkan pada kesadaran bahwa manusia sering melanggar bukan karena jahat, tetapi karena merasa tidak perlu tahu.
Novel Sewu Mayit karya Andika Reynaldo akhirnya tidak hanya menghadirkan cerita horor. Ia mengajak pembaca merenung tentang hubungan manusia dengan alam, dengan tradisi, dan dengan batas-batas yang selama ini dijaga bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Ketika batas itu dilanggar tanpa kesadaran, yang muncul bukan hanya bahaya, tetapi kehilangan arah.
Dan barangkali, yang paling menakutkan dari Sewu Mayit bukanlah pasarnya, melainkan kenyataan bahwa manusia sering merasa cukup aman untuk tidak lagi mendengarkan peringatan.